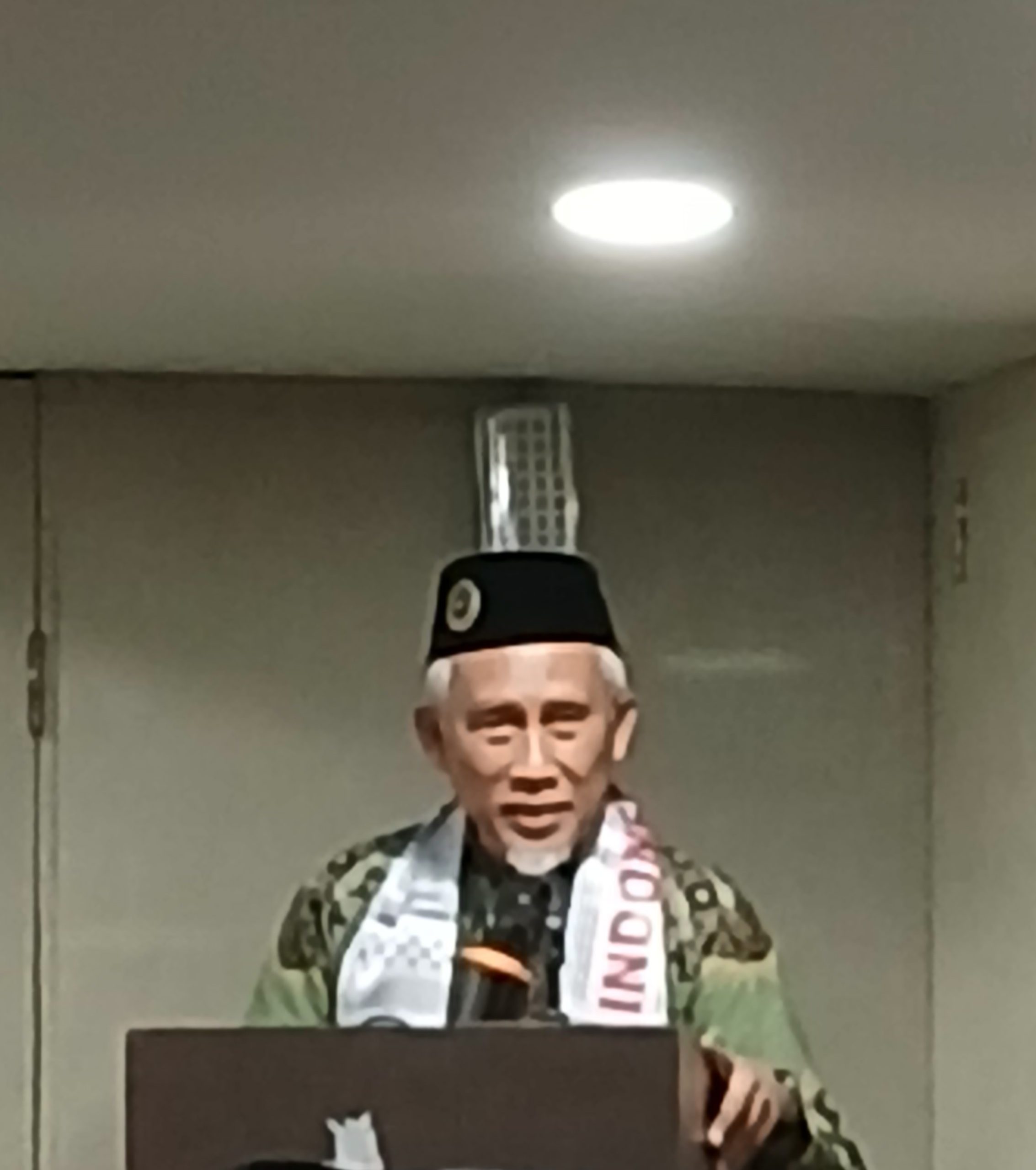sidikfokusnews.com. Jakarta — Perdebatan mengenai desain sistem pemilihan nasional kembali mengemuka seiring kritik tajam terhadap praktik pemilihan presiden secara langsung. Akademisi dan pakar sistem pemerintahan menilai, mekanisme pemilihan melalui musyawarah perwakilan berjenjang sebagaimana dirancang dalam UUD 18 Agustus 1945 justru lebih rasional, efisien, dan selaras dengan realitas geografis serta sosiologis Indonesia sebagai negara kepulauan.
Guru Besar ITS sekaligus pemerhati tata kelola negara, Daniel Mohammad Rosyid, menegaskan bahwa pemilihan eksekutif melalui perwakilan berjenjang berpotensi merekrut pemimpin yang lebih cakap dengan biaya politik yang jauh lebih rendah. Dalam pandangannya, pemilihan presiden oleh anggota MPR—yang berjumlah sekitar seribu orang sebagai representasi hasil musyawarah berlapis—merupakan mekanisme konstitusional yang dirancang untuk menjamin kebijaksanaan kolektif, bukan sekadar agregasi suara massal.
Menurut Daniel, perubahan konstitusi pasca-2002 yang melahirkan pemilihan presiden langsung justru menggeser prinsip musyawarah bil hikmah menjadi praktik pencoblosan massal oleh sekitar 160 juta pemilih yang, secara struktural, tidak memiliki tanggung jawab langsung terhadap kualitas keputusan kolektif tersebut. Dalam teori politik, kondisi ini dikenal sebagai rational ignorance, di mana pemilih tidak memiliki insentif memadai untuk memahami secara mendalam rekam jejak, kapasitas, dan visi pasangan calon.
Dari sisi logistik, pilpres langsung dinilai mendekati batas kemustahilan. Dengan lebih dari 800 ribu TPS yang tersebar di bentang geografis seluas Eropa, Indonesia dipaksa mengelola operasi pemilu raksasa di tengah tata kelola logistik yang kerap bocor dan rawan manipulasi. Sejumlah pakar kepemiluan menyebut kondisi ini bukan sekadar kompleks, melainkan cerminan dari “kegilaan logistik” yang berulang setiap lima tahun.
Masalah tidak berhenti pada aspek teknis. Di bilik suara, pemilihan presiden dan wakil presiden bukanlah proses seleksi sederhana. Bahkan jika pemilih dibekali curriculum vitae kandidat sekalipun, kompleksitas tugas kenegaraan tidak mudah diterjemahkan menjadi pilihan rasional dalam satu momen pencoblosan. Akibatnya, seleksi kepemimpinan nasional tunduk pada hukum statistik semata—the law of large numbers—dan efek oligarkis yang dijelaskan oleh Mancur Olson. Dalam konteks ini, fenomena pasangan calon “nomor tengah” yang kerap unggul dalam kontestasi tiga kandidat bukanlah kebetulan, melainkan konsekuensi psikologis pemilih massal.
Sebaliknya, para ahli tata negara menilai pemilihan wakil rakyat secara berjenjang lebih masuk akal. Pemilih di tingkat akar rumput relatif mengenal calon anggota DPRD kabupaten atau kota, baik dari rekam jejak maupun kedekatan sosial. Dari lembaga inilah perwakilan dapat dikirim ke DPRD provinsi, lalu ke DPR RI, termasuk pengisian unsur utusan daerah dan utusan golongan. Dalam desain ini, pemilihan langsung cukup dilakukan di tingkat lokal, sementara pengisian jabatan strategis lainnya berlangsung melalui mekanisme perwakilan yang teruji secara politik dan etis.
Pandangan kritis juga diarahkan pada dampak politik dari pilpres langsung. Sejumlah pengamat menyebut bahwa sistem pasca-amandemen UUD 2002 cenderung melahirkan pasangan presiden dan wakil presiden sebagai “petugas partai” yang terikat pada agenda oligarki pendanaan politik. Posisi presiden tidak lagi sebagai mandataris MPR yang menjalankan Garis-Garis Besar Haluan Negara, melainkan sebagai eksekutor kompromi kekuatan modal dan elite partai.
Dalam konteks ini, pernyataan bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto memahami secara mendalam cacat struktural pilpres langsung menjadi sorotan. Harapan publik mengarah pada konsistensi partai pengusungnya, Gerindra, untuk kembali menjadikan UUD 18 Agustus 1945 sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara, alih-alih terus bertumpu pada desain konstitusional hasil amandemen 2002 yang dinilai banyak kalangan lahir secara tergesa dan problematik.
Wacana ini menandai kebangkitan kembali diskursus besar tentang arah demokrasi Indonesia: apakah demokrasi dimaknai semata sebagai pemungutan suara langsung, atau sebagai proses permusyawaratan yang bertanggung jawab, berjenjang, dan berorientasi pada kualitas kepemimpinan nasional. Di titik inilah, perdebatan tidak lagi bersifat teknis, melainkan menyentuh jantung filsafat bernegara Republik Indonesia.
[ arf-6 ]