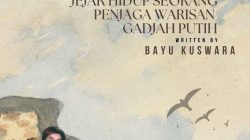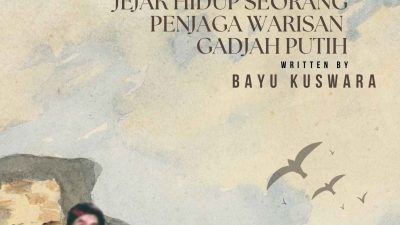sidikfokusnews.com.Tanjungpinang.-Dalam geliat arus pembangunan nasional, wajah Rempang kembali muncul dalam percaturan proyek besar negara. Kali ini, bukan karena penggusuran tanah adat seperti yang pernah terjadi, melainkan karena rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung di atas perairan Rempang yang disebut-sebut sebagai bagian dari program ekspor energi bersih ke Singapura.
Namun, rencana ini memantik pertanyaan fundamental dari kalangan adat dan budaya: apakah kebijakan ini hanya soal kilowatt dan dollar, atau ada konsekuensi lebih dalam terhadap warisan identitas, ruang hidup, dan marwah masyarakat Melayu?
Suara yang Mulai Layu dari Kursi Kekuasaan. Masyarakat Melayu, yang secara historis adalah tuan rumah negeri ini, kini justru menghadapi dilema klasik. Dalam struktur pemerintahan dan jabatan publik, lebih dari 80% pejabat di Kepri berlatar belakang Melayu. Namun, suara-suara yang dahulu lantang kini mulai pelan, bahkan menghilang dalam gema protokoler kekuasaan.
> “Pejabat 80% Melayu, tapi setelah menjabat, jadi layu,” keluh seorang tokoh adat dari Pulau Bintan.
“Dulu suara garang melebihi harimau, sekarang penuh alasan: takut kualat, takut menyinggung,”
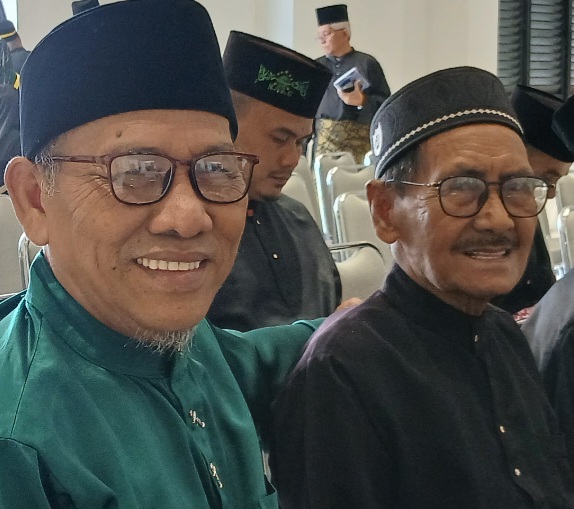
Yang menyedihkan bukan hanya diamnya mereka yang punya kuasa, tapi juga abainya mereka yang dulunya berjuang dengan semangat marwah. Ketika kekuasaan telah digenggam, suara rakyat justru ditinggalkan di belakang, sunyi dan tak didengar.
Mana Bugis? Saatnya Bahu-Membahu Tegakkan Kebenaran, Kebudayaan Melayu tak pernah berdiri sendiri. Dalam sejarah panjang kawasan ini, Bugis dan Melayu adalah dua serumpun yang saling menguatkan, berbagi sejarah, tanah, dan air mata perjuangan.
Kini, ketika tanah dan marwah kembali dipertaruhkan, muncul pertanyaan tajam:
> “Mana Bugis? Sudah saatnya bangkit bahu membahu dengan Melayu. Tegakkan kebenaran, lawan kezoliman. Jangan ikut menzolimi. Kita bisa kualat pada nenek moyang kita yang terkubur di tanah Melayu ini,”
Sejarah mencatat bahwa kerjasama Melayu dan Bugis telah membentuk struktur kekuasaan, pertahanan maritim, bahkan pusat-pusat peradaban di Kepulauan Riau. Maka, tantangan hari ini bukan hanya soal panel surya atau ekspor listrik, tapi soal bagaimana generasi pewaris budaya merawat warisan dan kehormatan itu.
Simbol Budaya Tanpa Daya. Ironisnya, di tengah polemik ini, banyak agenda budaya hanya menjadi simbol tanpa substansi. Haul Sultan Abdulrahman Mu’adzam Syah di Penyengat, yang seyogianya menjadi ajang konsolidasi semangat kebangsaan dan kebudayaan, kini tak lebih dari seremoni tahunan.
> “Tiada tokoh Melayu yang hadir bukan berarti tidak sepakat. Tapi jangan sampai budaya kehilangan daya karena sibuk menjadwalkan kesibukan,”
Pernyataan ini menyentil banyak tokoh. Karena budaya tidak akan hidup dengan seremoni semata. Ia butuh gerak, keberanian, dan perlawanan yang bijak terhadap kebijakan yang mengancam ruang hidup masyarakat adat.
Menurut Dr. Rizal Rahim, pakar budaya dan kearifan lokal dari Universitas Maritim Raja Ali Haji:
> “Kearifan lokal bukanlah penghambat pembangunan. Ia adalah mekanisme alami masyarakat dalam menjaga harmoni antara manusia, alam, dan kekuasaan. Jika pembangunan mengabaikan ini, maka yang lahir adalah ketimpangan, konflik, dan hilangnya identitas.”
Ia menambahkan bahwa kawasan pesisir seperti Rempang memiliki nilai ekologis dan spiritual tinggi. “Membangun tanpa menghitung ruh budaya adalah seperti membangun rumah tanpa pondasi,” ujarnya tegas.
Indonesia boleh saja bangga menjadi eksportir listrik bersih ke Singapura. Tapi perlu ditimbang, siapa yang diuntungkan dan siapa yang terdampak?
Menurut Ir. Baharuddin Saleh, pengamat kebijakan energi dan lingkungan:
> “Pembangunan PLTS skala ekspor di atas perairan adalah ide besar. Tapi harus jelas: siapa pemilik lahan perairan, bagaimana kompensasi sosialnya, dan apakah masyarakat lokal dilibatkan dalam manfaat ekonomi? Jika tidak, maka ini hanyalah kolonialisme energi gaya baru.”
Baharuddin menyarankan agar lokasi PLTN (Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir) diprioritaskan di pulau-pulau terluar seperti Pulau Nipah, yang berhadapan langsung dengan Singapura. “Lebih efisien dan strategis secara geopolitik,” ujarnya.
Budaya Sebagai Pilar Terakhir Perlawanan. Tengku Muhammad Fuad, menegaskan:
“Barang siapa berbaik-baik sangat dengan pejabat, walau pun bodoh dianggap hebat. Barang kali dia tak bodoh, dia hanya pejabat yang selalu dipandang hebat…”

Dengan nada satire, ia menohok situasi sekarang—di mana loyalitas kepada kekuasaan kerap mengalahkan keberpihakan pada rakyat.
Budaya, katanya, adalah benteng terakhir. “Melayu tidak hilang. Meski kayu diukir pahat, takkan besi disepuh emas. Meski terdesak, Melayu masih punya harga, marwah, dan semangat mempertahankan yang benar.”
Bukan Menolak Pembangunan, Tapi Merawat Kehormatan
Ini bukan tentang menolak pembangunan. Ini tentang memastikan pembangunan tidak mengorbankan akar budaya, tidak menghapus tapak sejarah, dan tidak melukai masyarakat adat.”(Arf)