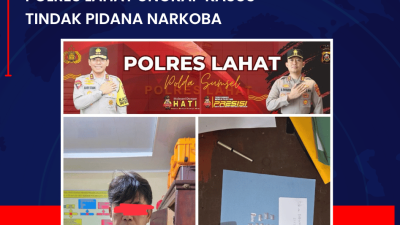sidikfokusnews.com-Tanjungpinang.— Kasus dugaan pemalsuan sertifikat tanah dengan tersangka Een Saputro dan beberapa rekannya terus menjadi sorotan publik. Polresta Tanjungpinang menegaskan komitmennya untuk menuntaskan perkara ini secara tuntas dan bertahap. Dalam keterangan resminya, Kapolresta Kombes Pol Hamam Wahyudi menyampaikan bahwa perkara utama yang saat ini ditangani lebih dulu adalah dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP. Sementara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) akan menyusul setelah proses hukum perkara pokok diputuskan.
Pernyataan tersebut memicu diskursus di tengah masyarakat dan kalangan praktisi hukum. Banyak yang mempertanyakan: apakah langkah memisahkan penanganan pemalsuan dan TPPU itu sah secara hukum? Apakah pemisahan ini berdampak pada efektivitas dan integritas proses hukum? Bagaimana seharusnya kasus-kasus seperti ini ditangani secara ideal?
Dr. Indra Giri Putra, pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, menjelaskan bahwa dalam sistem hukum Indonesia, pendekatan untuk mendahulukan penyelesaian perkara pokok sebelum masuk ke ranah TPPU merupakan praktik yang umum dan sah secara hukum.
“Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan adalah delik formil. Untuk mengajukan TPPU, penegak hukum harus bisa membuktikan terlebih dahulu bahwa memang benar telah terjadi tindak pidana asal. Dalam hal ini, pemalsuan sertifikat merupakan tindak pidana asal atau predicate crime yang menjadi dasar TPPU,” ujarnya.
Menurut Indra, tanpa pembuktian terhadap predicate crime, penuntutan terhadap TPPU bisa gugur di pengadilan karena tidak memiliki dasar yang sah. Oleh karena itu, pemisahan tahapan ini justru merupakan bentuk kehati-hatian penegak hukum.
Namun demikian, ia juga mengingatkan bahwa penanganan harus dilakukan secara paralel dalam aspek penyelidikan dan penyitaan aset, agar tidak kehilangan jejak aliran uang yang diduga berasal dari kejahatan pokok.
“Jika tidak dilakukan dengan cermat, pelaku bisa lebih dulu menghilangkan atau memindahkan asetnya, yang kemudian menyulitkan penegakan TPPU,” tambahnya.
Sementara itu, dari perspektif hukum acara pidana, Prof. Evi Hartanti, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjadjaran, menjelaskan bahwa pelepasan dua tersangka yang dilakukan oleh penyidik Polresta Tanjungpinang merupakan langkah yang memang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
“Penahanan dalam KUHAP itu ada batas waktunya. Jika masa penahanan habis dan berkas belum lengkap (P-19), maka penahanan tidak bisa diperpanjang begitu saja. Jika penyidik menahan lebih lama dari waktu yang ditentukan tanpa dasar hukum, itu bisa menjadi pelanggaran hak asasi manusia,” kata Prof. Evi.
Namun ia menekankan bahwa pelepasan karena batas waktu bukan berarti tersangka bebas. Status tersangka tetap melekat, dan penyidikan terus berjalan. Penyidik bahkan bisa kembali menahan jika terdapat alat bukti baru atau pengembangan perkara yang menuntut tindakan tersebut.
“Penegakan hukum tidak selalu identik dengan penahanan. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa proses penyidikan tetap berjalan dan transparan,.
Kasus pemalsuan dokumen tanah yang mengarah ke TPPU bukanlah hal baru di Indonesia. Menurut catatan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sektor agraria dan pertanahan merupakan salah satu sektor rawan yang kerap dijadikan sarana pencucian uang.
Dr. Wahyudi Djafar, peneliti senior di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), menyebut bahwa pemalsuan dokumen pertanahan bukan hanya berdampak pada legalitas hak milik, tetapi juga menjadi celah untuk mencuci dana hasil kejahatan.
“Jika hasil pemalsuan digunakan untuk menjual, menggadaikan, atau mencairkan aset lalu dialirkan ke rekening-rekening pribadi atau badan usaha, maka unsur TPPU sudah masuk. Tapi memang pembuktiannya tidak sederhana dan membutuhkan kerja sama lintas institusi seperti PPATK, BPN, dan penyidik,.
Ia mendukung langkah Polresta Tanjungpinang yang memilih mendahulukan perkara Pasal 263 KUHP, namun menyarankan agar proses pengumpulan data dan analisis aliran dana dilakukan secara paralel. Menurutnya, “Sistem split prosecution ini tidak masalah, asal terkoordinasi dengan baik dan ada pengamanan aset.
Di sisi lain, sosiolog hukum dari Universitas Andalas, Dr. Rika Hastuti, mengingatkan bahwa proses hukum yang terlalu teknokratis bisa mengikis kepercayaan publik jika tidak disertai komunikasi yang terbuka dan akuntabel.
“Warga yang menjadi korban pemalsuan ingin keadilan, bukan sekadar proses hukum yang sah di atas kertas. Jika tersangka dilepaskan sementara publik merasa dirugikan, maka perlu komunikasi yang menjelaskan posisi hukum secara gamblang,.
Ia juga menyarankan agar penegak hukum membuka ruang bagi partisipasi publik dan korban untuk mengikuti jalannya proses hukum, agar rasa keadilan tidak semata diserahkan kepada aparat, melainkan juga melibatkan masyarakat sebagai pengawas sosial.
Kasus pemalsuan sertifikat tanah di Tanjungpinang telah membuka kembali perbincangan tentang sinkronisasi antara hukum pidana umum dan tindak pidana khusus seperti TPPU. Para ahli sepakat bahwa pendekatan bertahap—menyelesaikan Pasal 263 KUHP terlebih dahulu—merupakan langkah konstitusional dan strategis. Namun, keberhasilan langkah ini sangat bergantung pada keterpaduan antar lembaga, kehati-hatian dalam pengamanan aset, serta konsistensi dalam menindaklanjuti ke tahapan TPPU.
Dalam kasus ini, publik menunggu lebih dari sekadar proses: mereka menanti tegaknya keadilan substantif, pemulihan hak-hak masyarakat, dan akuntabilitas para pelaku yang merugikan tidak hanya lembaga negara, tetapi juga warga sipil yang hak atas tanahnya tercederai.”TRSF)