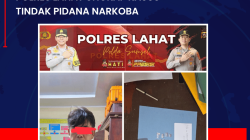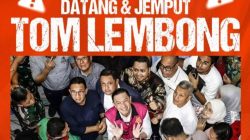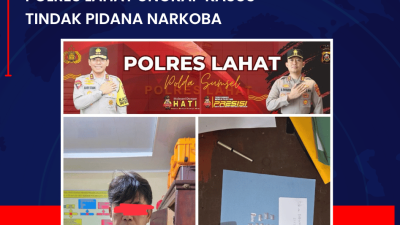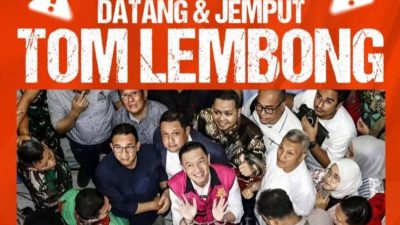sidikfokusnews.com-Jakarta — Ketika Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian yang dipimpin Prof. Jimly Asshiddiqie baru mulai mengatur jadwal rapat mingguan, Mahkamah Konstitusi justru melesat lebih dulu dengan keputusan historis yang mengguncang lanskap birokrasi Indonesia. Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025, yang dibacakan 13 November 2025, seketika menyapu bersih ruang abu-abu yang selama bertahun-tahun menjadi celah bagi polisi aktif untuk menjabat di posisi sipil.
Melalui putusan itu, MK menegaskan bahwa personel Polri aktif tidak boleh lagi menduduki jabatan sipil apa pun. Frasa “penugasan Kapolri” dalam aturan lama—yang selama ini menjadi jalan halus menuju kursi-kursi strategis seperti KPK, BNN, hingga BSSN—dinyatakan bertentangan dengan konstitusi. Pesannya sederhana namun tajam: seragam tidak boleh lagi berada di arena yang diperuntukkan bagi sipil.
Ahli hukum tata negara melihat langkah MK ini sebagai koreksi struktural yang sudah terlalu lama ditunda. Menurut mereka, apa yang diputuskan MK bukan sekadar pembacaan normatif undang-undang, melainkan “penyelamatan arsitektur ketatanegaraan.” Polisi aktif di jabatan sipil dianggap menimbulkan distorsi kewenangan, mengaburkan garis batas sipil-kepolisian, dan membuka risiko penyalahgunaan kekuasaan karena tidak ada mekanisme akuntabilitas yang benar-benar tegas. “Putusan MK ini seperti mengembalikan fondasi yang miring tanpa perlu menunggu panitia teknis,” ujar seorang guru besar hukum administrasi yang enggan disebutkan namanya.
Di mata pemerhati tata negara, putusan tersebut menjadi pengingat bahwa prinsip civil supremacy bukanlah jargon demokrasi, melainkan syarat dasar agar negara modern berfungsi dengan benar. Mereka menilai MK telah menjalankan perannya secara ideal: mengoreksi penyimpangan, mengembalikan logika konstitusi, dan menutup pintu bagi pembiasan tafsir yang selama ini tumbuh melalui kebijakan internal. Sejumlah pakar juga menilai dalil pemerintah tentang resiprokal ataupun alasan “aturan internal Polri” memang tidak sejalan dengan prinsip hukum publik. Jika jabatan itu sipil, maka ia harus tunduk pada struktur sipil, bukan pada institusi berseragam.
Dalam konteks ini, kemunculan putusan MK justru menjadi ironi bagi Komisi Reformasi Kepolisian yang baru berusia beberapa hari. Komisi yang dipimpin Prof. Jimly—yang beranggotakan sepuluh tokoh dari berbagai disiplin—masih menyusun peta jalan, sementara MK sudah memotong salah satu simpul paling krusial dalam reformasi kepolisian. Para ahli menyebut ini sebagai “wake-up call” bahwa reformasi kepolisian tidak cukup disandarkan pada rapat dan rencana, tetapi harus dimulai dari perombakan prinsipil atas hubungan kekuasaan.
Sejumlah analis pun membaca langkah MK sebagai pesan politik-konstitusional: reformasi polisi bukan urusan polisi semata. Negara, melalui lembaga yudisial tertinggi dalam ranah konstitusi, turun tangan untuk memastikan batas antara kekuasaan sipil dan kepolisian kembali ditegakkan. Dengan kata lain, MK sedang menutup ruang kolonisasi birokrasi sipil oleh institusi yang berkarakter komando.
Tokoh nasional yang meminta namanya tidak dicantumkan mengingatkan, negara ini terlalu sering dikuasai oleh saling intai kekuasaan, saling berebut pengaruh, dan saling merekayasa kebijakan strategis tanpa memikirkan kepentingan jangka panjang. “Ya Allah, perbaikilah negeri ini dari mereka yang mampu mengubah yang buruk menjadi baik, tetapi memilih jalan propaganda. Kembalikan mereka ke prinsip yang benar,” ujarnya.
Dalam dinamika politik dan hukum yang bergerak cepat ini, publik kini menunggu bab berikutnya. Apakah Komisi Reformasi Kepolisian akan memanfaatkan putusan MK sebagai fondasi, atau justru terseret dalam tarik-menarik kepentingan struktural? Apakah pemerintah menerima konsekuensi penuh, termasuk terhadap posisi-posisi pejabat aktif yang kini terkena dampaknya?
Sementara perdebatan terus berlangsung, satu hal menjadi jelas: sembilan hakim MK telah mendahului segalanya, menanamkan garis tegas yang lama kabur. Kepolisian dituntut kembali ke ranah konstitusionalnya, birokrasi sipil mendapatkan kembali hak otonominya, dan reformasi yang semula tampak sebagai wacana kini berubah menjadi langkah konkret yang memaksa negara menata ulang dirinya sendiri.
Dan bangsa ini—dengan segala keanehannya—mungkin baru pertama kali melihat bagaimana reformasi dimulai bukan dari gedung eksekutif ataupun ruang rapat komisi, melainkan dari palu konstitusi yang akhirnya digunakan sebagaimana mestinya.
arf-6