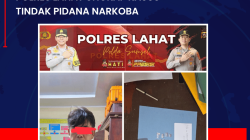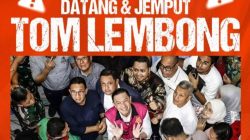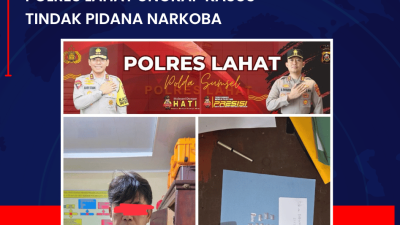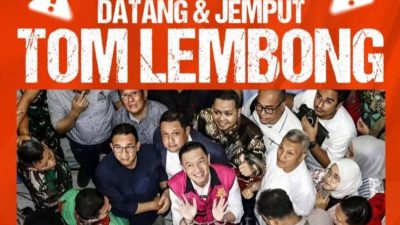sidikfokusnews.com-Jakarta. — Hingga Juli 2025, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mencatat telah menetapkan 333.687 hektare lahan sebagai hutan adat yang tersebar di 160 unit wilayah di seluruh Indonesia. Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat, Julmansyah, mengatakan pengakuan ini memberi manfaat langsung bagi lebih dari 83.000 kepala keluarga masyarakat adat.
“Sebanyak 5.176 hektare saat ini sedang dalam proses pencabutan izin hutan kemasyarakatan untuk kemudian dikukuhkan sebagai hutan adat,” ujarnya, Jumat (8/8/2025). Langkah ini, kata dia, sesuai amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 yang menegaskan hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara.
Data Kemenhut menunjukkan tren percepatan sejak 2019, dengan lonjakan penetapan di 2022 hampir 80.000 hektare, 2023 lebih dari 90.000 hektare, dan 2024 mencapai 88.000 hektare. Saat ini pengakuan telah menjangkau 41 kabupaten di 19 provinsi, dengan Kalimantan Barat menjadi yang terluas (117.000 hektare), diikuti Kalimantan Tengah (68.000 hektare), Papua Barat, Sumatera Utara, dan Papua. Potensi tambahan masih terbuka dengan luasan indikatif sekitar 762.000 hektare, sebagian besar di Kalimantan Utara.
Namun, Kepulauan Riau (Kepri) sama sekali tidak muncul dalam daftar tersebut. Padahal, di wilayah ini pernah mencuat perjuangan masyarakat adat, seperti di Pulau Rempang yang menjadi sorotan akibat konflik tata ruang dan investasi.

Kerumitan ini, menurut pengamat kehutanan dan kebijakan agraria Universitas Indonesia, Dr. Wira Santosa, disebabkan oleh sifat geografis dan tata ruang Kepri. “Hutan adat di kepulauan kerap tumpang tindih dengan rencana zonasi laut dan pesisir. Mekanisme pengakuannya membutuhkan pendekatan berbeda dibandingkan hutan daratan luas. Tanpa itu, hak masyarakat adat di wilayah maritim rawan terpinggirkan oleh proyek strategis nasional,” jelasnya.
Sosiolog hukum agraria Universitas Andalas, Prof. Siti Marwah, menekankan bahwa lambatnya pengakuan di Kepri membuat akses masyarakat terhadap sumber daya alam semakin rapuh. “Jika hak pengelolaan tradisional tidak diakui secara hukum, mereka bisa tergeser secara fisik maupun kultural. Ketiadaan legalitas juga berarti kehilangan alat untuk membela diri di hadapan hukum,” katanya.
Perdebatan di lapangan menambah kompleksitas. Sebagian pihak menilai lembaga adat sipil seperti Lembaga Adat Melayu (LAM) tidak memiliki legitimasi formal untuk menuntut tanah adat atau ulayat karena statusnya bukan lembaga keturunan kerajaan. Tanah adat sendiri memiliki perbedaan mendasar dengan tanah kesultanan: tanah ulayat bersifat komunal dan tidak bisa diwariskan atau diperjualbelikan, sedangkan tanah kesultanan bersifat privat dan dapat dipindahtangankan.
Pertanyaan kunci pun muncul: adakah komunitas masyarakat adat yang diakui secara legal oleh negara di Kepri? Data menunjukkan tidak ada penetapan resmi di provinsi ini. Masyarakat Hukum Adat Suku Sakai Bathin Sobangha memang telah diakui di Provinsi Riau, khususnya di Bengkalis, Rokan Hilir, dan Dumai, bahkan memiliki wilayah budaya yang beririsan secara geografis dengan Kepri. Namun secara administratif, pengakuan tersebut belum menjangkau Kepri.
Para pakar sepakat bahwa meskipun payung hukum seperti PP Nomor 23 Tahun 2021 dan Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021 telah ada, penerapannya masih timpang di daerah kepulauan. Kepri dinilai membutuhkan kebijakan afirmatif yang mengakomodasi karakter sosial-ekologis kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Tanpa langkah tersebut, peluang pengakuan hutan adat di Kepri akan terus tertinggal, meskipun spiritnya sejalan dengan amanat konstitusi.
Absennya Kepri dari peta nasional hutan adat menjelang peringatan 80 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa pengakuan hak masyarakat adat belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Bagi banyak komunitas di provinsi ini, kemerdekaan yang hakiki belum sepenuhnya tiba di tanah leluhur mereka.”(timredaksiSF)