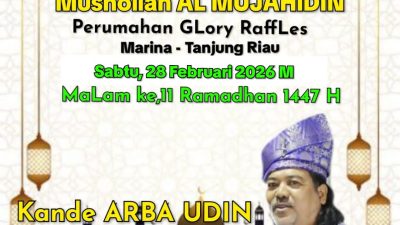sidikfokusnews.com – Batam – Dalam momen peringatan kemerdekaan, muncul berbagai suara dan pemikiran yang mewarnai ruang diskusi masyarakat. Sebagian orang menegaskan rasa syukur atas nikmat kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata para pendahulu. Kemerdekaan diyakini sebagai pintu menuju kehidupan yang lebih makmur, sejahtera, dan berkeadilan. Namun, rasa syukur ini tidak menutup kemungkinan munculnya kegelisahan atas realitas sosial dan kebijakan negara yang dirasakan membebani rakyat.
Isu pajak misalnya, menjadi sorotan yang kerap menimbulkan perdebatan. Ada yang menilai bahwa kenaikan pajak, bahkan hingga lebih dari 400 persen, justru menekan masyarakat kecil yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sementara itu, opini kritis terhadap kebijakan semacam ini sering dianggap wajar dan semestinya tidak dibungkam. Bagi sebagian kalangan, ketika rakyat menyuarakan kegelisahan, hal tersebut bukanlah bentuk perlawanan yang mengancam, melainkan ekspresi kepedulian terhadap jalannya negara.

Di sisi lain, ada pula pandangan yang menyoroti persoalan kemiskinan dari sudut pandang kemalasan. Muncul ungkapan bahwa kemiskinan semata-mata bukanlah akibat dari kebijakan negara, melainkan karena sikap malas individu yang enggan berjuang. Narasi ini kemudian dikritik, karena realitas di lapangan menunjukkan banyak orang yang setiap hari berusaha keras mencari pekerjaan, bahkan berkeliling dari kawasan industri ke kawasan industri, namun tetap kesulitan mendapatkan kesempatan. Dengan demikian, menyederhanakan kemiskinan hanya sebagai akibat kemalasan adalah bentuk ketidakadilan terhadap perjuangan rakyat kecil.
Perbandingan dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam pun turut hadir dalam diskusi. Ada yang menyoroti bahwa di negara-negara tersebut kebebasan warganya lebih terbatas, termasuk dalam hal berbicara di media sosial, berkumpul, atau beribadah larut malam. Namun, membandingkan kemajuan sebuah bangsa dengan bangsa lain tentu tidak selalu relevan dengan konteks persoalan yang dihadapi dalam negeri. Masyarakat yang kritis terhadap kebijakan negara memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pendapatnya tanpa harus selalu dibandingkan dengan sistem negara lain.
Diskusi kemudian bergeser kepada peran guru dan dunia pendidikan dalam menjawab problematika pengangguran. Muncul pertanyaan kritis: apakah guru dapat dikatakan berhasil jika murid-muridnya mampu mengatasi problem kehidupan dan mandiri, ataukah keberhasilan guru diukur dari banyaknya murid yang sukses mendapatkan pekerjaan? Dalam hal ini, dijelaskan bahwa guru, kyai, maupun ulama memiliki tanggung jawab utama untuk mengajarkan ilmu, bukan menjamin kesejahteraan hidup murid di masa depan. Keberhasilan seorang guru bukan diukur dari status ekonomi muridnya kelak, melainkan dari sejauh mana murid mampu menyerap ilmu, mengembangkan akhlak, dan memiliki bekal pengetahuan yang bermanfaat untuk kehidupannya.
Namun, hal ini tidak berarti peran guru dan akademisi berhenti sebatas ruang kelas. Guru dan dosen juga diharapkan dapat membuka peluang, memperluas jejaring, dan menjadi bagian dari solusi untuk mengurangi pengangguran. Setidaknya, kehadiran mereka dapat menginspirasi murid agar lebih mandiri, kritis, dan tidak menyerah menghadapi tantangan zaman.
Percakapan yang berkembang tersebut pada akhirnya merefleksikan wajah kehidupan berbangsa: ada rasa syukur atas kemerdekaan, ada kritik terhadap kebijakan negara, ada pandangan yang menyalahkan individu, ada pula suara yang membela rakyat kecil. Semuanya menunjukkan dinamika berpikir masyarakat Indonesia yang semakin terbuka dan plural. Diskusi ini sekaligus mengingatkan bahwa membangun bangsa tidak hanya soal kebijakan pemerintah, tetapi juga keterlibatan seluruh elemen—mulai dari guru, ulama, akademisi, hingga masyarakat biasa—dalam menata kehidupan yang lebih adil, makmur, dan bermartabat.
Editor : Nursalim Turatea